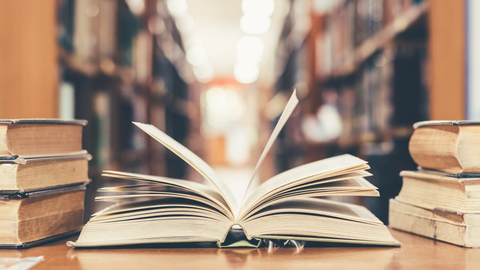
Fenomena penyitaan buku-buku ideologis dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah memicu tanya besar: Apakah negara mulai takut terhadap pikiran kritis yang lahir dari bacaan? Aksi aparat yang menyita karya-karya seperti Pemikiran Karl Marx, Anarkisme, hingga sastra karya Pramoedya Ananta Toer dalam beberapa razia polisi terbaru, menyulut kekhawatiran sipil bahwa pengetahuan kini dibatasi.
Kementerian HAM menilai tindakan penyitaan itu bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menyebut bahwa dalam menangani demonstrasi, aparat harus menjaga prinsip transparansi dan menghormati kebebasan intelektual warga. Namun kenyataannya, praktik di lapangan masih jauh dari semangat tersebut. Buku-buku tetap disita, diskusi dibubarkan, dan ruang berpikir kritis perlahan dibatasi atas nama keamanan dan ketertiban.
Pada 18 September 2025, Direktorat Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur menyita puluhan buku yang diklaim berkaitan dengan ideologi radikal dari seorang tersangka demonstran. Buku-buku itu kemudian dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan provokasi. Aparat beralasan bahwa konten buku tersebut dapat dianggap sebagai “bahan inspirasi” bagi tindakan anarkis. Namun kritik muncul bahwa penyitaan buku tidak otomatis menyimpulkan pembacaannya berdampak langsung pada tindakan kriminal.
Kasus ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan soal kebebasan berekspresi, tetapi juga mengguncang dunia pendidikan yang selama ini menjadi ruang aman bagi lahirnya pemikiran kritis. Jika bacaan bisa disalahartikan sebagai ancaman, bagaimana nasib kampus dan sekolah yang seharusnya menjadi tempat bertumbuhnya gagasan bebas?
Selama ini, kampus dan sekolah dianggap sebagai ruang terbuka pemikiran atau wadah bagi mahasiswa dan siswa mendiskusikan berbagai gagasan, termasuk gagasan kritis. Namun saat buku-buku yang dianggap ideologis disita, ruang tersebut terasa terancam menyusut. Pembatasan terhadap bahan bacaan justru menimbulkan kekhawatiran baru, bahwa lembaga pendidikan bisa kehilangan fungsinya sebagai tempat berkembangnya pandangan yang beragam dan independen.
Sejarawan dan pengamat pendidikan menyebut bahwa sensor buku pernah menjadi alat kekuasaan di masa lampau. Pada era Orde Baru, ribuan karya dinyatakan “berbahaya” dan dilarang peredarannya karena dinilai bertentangan dengan rezim. Tindakan tersebut mencerminkan ketakutan lama terhadap munculnya narasi-narasi alternatif yang dapat menggoyahkan status quo.
Dalam konteks pendidikan, tindakan seperti ini tidak hanya menyangkut urusan hukum, tetapi juga arah pembentukan karakter bangsa. Pendidikan seharusnya menjadi arena kebebasan berpikir, tempat di mana ide diuji, bukan dibungkam. Ketika siswa dan mahasiswa dibatasi dari bacaan tertentu, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar memilah, mengkritik, dan memahami perbedaan. Padahal, justru dari perbedaan sudut pandang itulah lahir kemampuan berpikir kritis dan empati sosial.
Buku-buku dengan muatan ideologis tidak serta merta berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika masyarakat dibiarkan buta terhadapnya tanpa pemahaman yang kontekstual. Menutup akses bacaan justru membuka ruang bagi kesalahpahaman. Dalam dunia pendidikan, tugas guru dan dosen bukan melarang bacaan tertentu, melainkan membimbing pembacanya agar mampu menafsirkan isi secara kritis dan rasional.
Di sisi lain, aparat menegaskan bahwa penyitaan buku harus berdasar pada kaidah hukum dan relevansi dengan konteks peristiwa. Bila buku memang terbukti dipakai sebagai alat propaganda dalam aksi kriminal, mereka berpendapat bahwa tindakan penyitaan bisa dibenarkan. Namun, persoalannya menjadi kompleks ketika setiap teks yang berbeda pandangan langsung dicap berbahaya. Di titik ini, garis antara “keamanan” dan “ketakutan terhadap pengetahuan” menjadi sangat tipis.
Negara seharusnya tidak takut pada rakyat yang berpikir. Pemerintah yang bijak justru mendukung warganya untuk kritis, karena dari sanalah lahir kemajuan. Membatasi akses terhadap buku sama saja dengan menolak kemungkinan bangsa untuk berkembang. Ketika literasi dikekang, yang tumbuh bukan keamanan, melainkan kebodohan yang terpelihara.
Akhirnya, pendidikan harus tetap menjadi ruang di mana gagasan diuji, diperdebatkan, dan tidak dikekang oleh batas-batas ideologi. Bila buku-buku yang dianggap “kontroversial” terus dipersekusi, maka tantangan terbesar generasi mendatang bukan hanya soal apa yang mereka baca, tetapi siapa yang berani mempertanyakan. Sebab, ketika pengetahuan dibatasi, kebodohan justru tumbuh subur, dan di situlah bahaya sesungguhnya.


