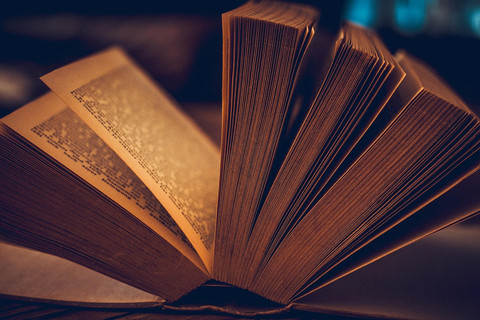
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)
Ayat tersebut menjadi kalimat pertama yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mafhum, pada saat itu Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi (tidak bisa membaca dan menulis). Namun justru itulah keistimewaannya. Allah memulai risalah Islam dengan perintah sederhana: “Iqra” (Bacalah!). Bukan sekadar ajakan mengeja huruf atau memahami teks. Ia adalah panggilan universal untuk mengaktifkan kesadaran, membuka wawasan, dan memahami makna kehidupan.
Menariknya Allah tidak memerintahkan “belajarlah membaca,” karena manusia sejatinya telah dibekali potensi dan akal untuk melaksanakan perintah itu. Artinya, setiap manusia memiliki kemampuan dasar untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Asalkan mau menggunakan akalnya.
Namun pemaknaan perintah sederhana itu tergantung pada siapa diri kita. Jika berpikir sempit, maka hanya berhenti di kalimat, “Saya kan tidak bisa membaca, kok disuruh baca.” Sebaliknya, jika berpikir lebih dalam akan langsung berusaha mencari cara untuk mampu membaca. Karena membaca bukan sekadar mengenal huruf, tapi mengenal kehidupan.
Literasi sebagai Kunci Kehidupan
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan tingkat literasi rendah. Padahal literasi bukan hanya sekadar membaca teks, melainkan juga membaca situasi, membaca masalah, dan membaca tanda-tanda zaman. Literasi adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menafsirkan realitas agar tidak terjebak dalam arus informasi yang salah.
Tanpa tradisi membaca, sulit bagi kita untuk melahirkan solusi yang bijak. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mengkritik, menghujat, atau menyalahkan, ketimbang memaknai persoalan secara mendalam.
Ketika literasi tumbuh, masyarakat menjadi lebih bijak dalam bersikap. Mereka mampu memilah mana yang fakta dan mana yang opini, mana yang membangun dan mana yang menyesatkan. Orang yang literat tidak akan cepat bereaksi, tetapi akan terlebih dahulu memahami konteks sebelum berkomentar atau bertindak. Masyarakat yang gemar membaca akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan beradab.
Lebih jauh lagi, literasi menjadi kunci utama untuk menghindari perpecahan dan salah paham. Dalam konteks sosial dan politik, literasi membantu kita memahami bahwa tidak semua perbedaan pandangan harus dihadapi dengan pertengkaran. Dengan literasi seseorang akan mampu melihat berbagai sisi dari satu masalah, menimbang data dan fakta sebelum menarik kesimpulan. Di sinilah letak kekuatan membaca, bukan sekadar membuka buku, tetapi membuka cara pandang baru terhadap kehidupan.
Media Sosial Menjadi Ruang Kritik Tanpa Solusi
Mari kita tengok realitas masyarakat hari ini. Kita hidup di era media sosial, hampir setiap isu publik menjadi bahan perdebatan panjang. Dari politik, ekonomi, pendidikan, sampai olahraga, semua ramai dibicarakan. Sayangnya, diskusi lebih sering berubah menjadi ajang hujatan, kritik tanpa solusi, atau sekadar keluhan. Tidak sedikit yang bahkan menikmati kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah hiburan. Ini adalah bentuk nyata krisis literasi digital.
Ironisnya, banyak komentar tajam justru keluar dari mereka yang tidak memahami duduk persoalan sebenarnya. Mereka membaca sepenggal informasi, langsung beropini dan menyebarkannya tanpa verifikasi. Akibatnya, ruang publik kita dipenuhi oleh kebisingan, bukan kebijaksanaan.
Inilah dampak rendahnya literasi. Sikap mudah bereaksi tanpa membaca secara utuh, mencerminkan betapa dangkalnya kesadaran berpikir di dunia digital. Kita terbiasa menarik kesimpulan hanya dari judul berita bukan isi, dari caption singkat atau potongan video bukan keseluruhan konteks. Tanpa membaca utuh, kita mudah terjebak hoaks, tersulut emosi, dan gagal memberi kontribusi positif. Padahal, di balik setiap peristiwa selalu ada sisi yang tidak terlihat.

Lebih dari itu, media sosial seharusnya menjadi ruang dialog, bukan arena pertempuran ego. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menggunakan platform ini untuk berbagi gagasan, memperluas wawasan, dan memperkuat solidaritas sosial. Untuk sampai ke sana dibutuhkan kesadaran kolektif untuk tidak berhenti pada kritik, melainkan bergerak menuju solusi. Karena bangsa besar bukanlah bangsa yang pandai mencela, tetapi bangsa yang mau belajar dan berbenah.
Membaca Realitas dengan Bijak
Membaca bukan hanya aktivitas akademik. Membaca juga berarti memahami realitas di sekitar kita. Petani akan membaca tanda-tanda cuaca sebelum menanam. Pedagang akan membaca tren pasar sebelum menentukan harga. Pemimpin bijak akan membaca kondisi masyarakat sebelum mengambil keputusan.
Namun di era media sosial, kita lebih suka membaca potongan, bukan keseluruhan. Kita hanya membaca sebagian, lalu cepat-cepat menarik kesimpulan. Padahal, untuk menemukan solusi, kita harus membaca secara menyeluruh.
Contoh sederhana misalnya masalah banjir. Jika hanya berhenti pada keluhan, musibah akan terulang setiap tahun. Tapi jika membaca akar masalahnya, seperti kerusakan lingkungan, drainase buruk, tata ruang yang salah, maka solusi bisa ditemukan.
Selain itu, membaca juga merupakan aktivitas spiritual. Ketika kita membaca alam, membaca kejadian, membaca tanda-tanda kehidupan, kita sedang berdialog dengan kebesaran Tuhan. Membaca adalah cara manusia memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan Penciptanya.
Setiap perintah Tuhan mengandung pesan pembelajaran. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, bisa jadi itu adalah “teks kehidupan” yang sedang menunggu untuk dibaca. Sayangnya, banyak yang berhenti pada keluhan, bukan pada pemahaman. padahal setiap ujian selalu membawa hikmah, sebagaimana setiap tulisan membawa makna bagi pembacanya.
Perintah “Bacalah” adalah perintah untuk selalu mencari pemahaman mendalam. Dari membaca lahir ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan lahir solusi.
Kita bisa lihat pada kasus naiknya harga cabai. Reaksi publik di media sosial biasanya penuh keluhan dan menyalahkan pemerintah atau pedagang. Padahal jika dibaca lebih dalam, penyebabnya ada di distribusi, pasokan, dan infrastruktur. Solusi jangka panjang bisa berupa gudang pendingin (cool storage), manajemen distribusi, dan edukasi konsumen.
Rendahnya literasi juga membuat masyarakat rentah terjebak hoaks. Judul bombastis langsung dipercaya tanpa dicek. Kalimat provokatif langsung disebar tanpa dipahami. Inilah ancaman serius bagi bangsa.
Maka, membangun budaya membaca harus menjadi prioritas. Tidak hanya membaca buku, tapi juga membaca data, membaca kebijakan, dan membaca arah zaman. Literasi digital juga penting, agar masyarakat tidak mudah terjebak arus informasi yang menyesatkan.
Perintah “Bacalah!” dalam QS. Al-‘Alaq adalah panggilan abadi bagi umat manusia. Bacalah bukan sekadar perintah membaca buku, tetapi membaca realitas, membaca tanda, membaca kehidupan.
Di tengah derasnya arus media sosial, mari kita tingkatkan literasi. Jangan hanya sibuk mengkritik tanpa solusi. Jangan terjebak pada kesalahan kecil. Fokuslah pada tujuan besar.
Dengan membaca secara mendalam, kita bisa menemukan arah, menghindari kesalahan, dan menemukan solusi. Itulah makna sejati dari perintah “Bacalah!” 1400 tahun silam yang masih relevan hingga hari ini.
Maka, “Bacalah!” bukan sekedar huruf di halaman, tapi juga pesan di balik setiap peristiwa. Karena dari membaca, kita belajar berpikir. Dari berpikir, kita belajar memahami. Dan dari memahami, kita menemukan jalan menuju kebijaksanaan.
Fokus pada Tujuan, Bukan Kesalahan Kecil
Mari kita akhiri dengan ilustrasi sederhana. Bayangkan saat berjalan kita menemukan papan penunjuk arah bertuliskan “Bleok Knan.” Jelas salah tulis, seharusnya “Belok Kanan”).
Orang yang berpikir dangkal akan sibuk mempersoalkan salah tulisannya. Ia mungkin memotret, mengunggah ke media sosial, lalu menertawakan. Tapi ia tetap bingung, tidak sampai tujuan.
Sebaliknya, orang yang melek literasi akan langsung memahami maksudnya. Ia langsung belok kanan, sampai lebih cepat, tanpa membuang waktu. Ia tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan kecil, sibuk menghujat, tanpa bergerak maju.
Inilah makna literasi. Membaca bukan hanya mengeja kata, tapi memahami arah, lalu bertindak untuk sampai pada tujuan. Karena pada akhirnya, keberhasilan tidak ditentukan seberapa sering kita mengkritik, melainkan seberapa cepat kita memahami makna dan mengambil langkah.


